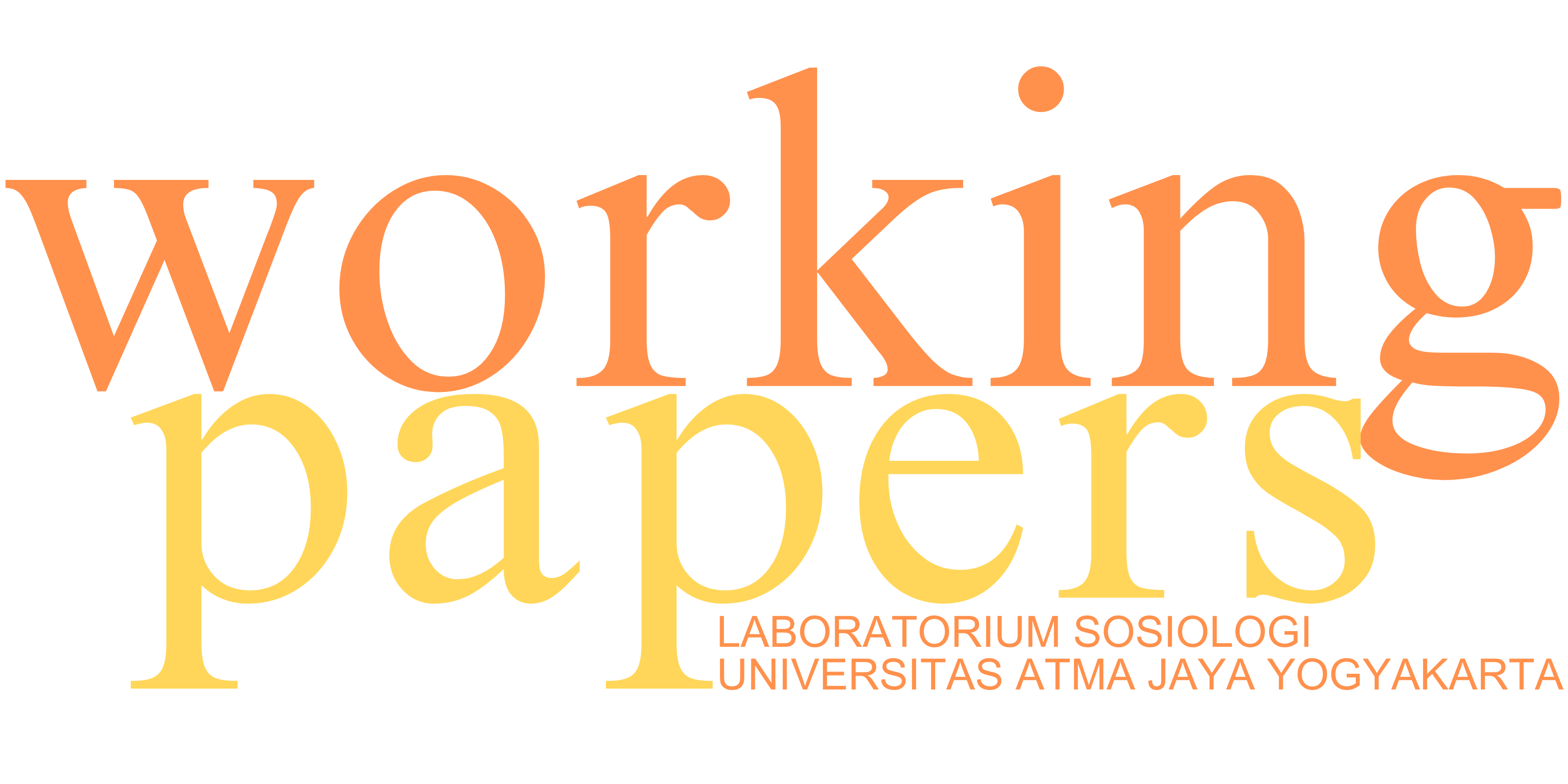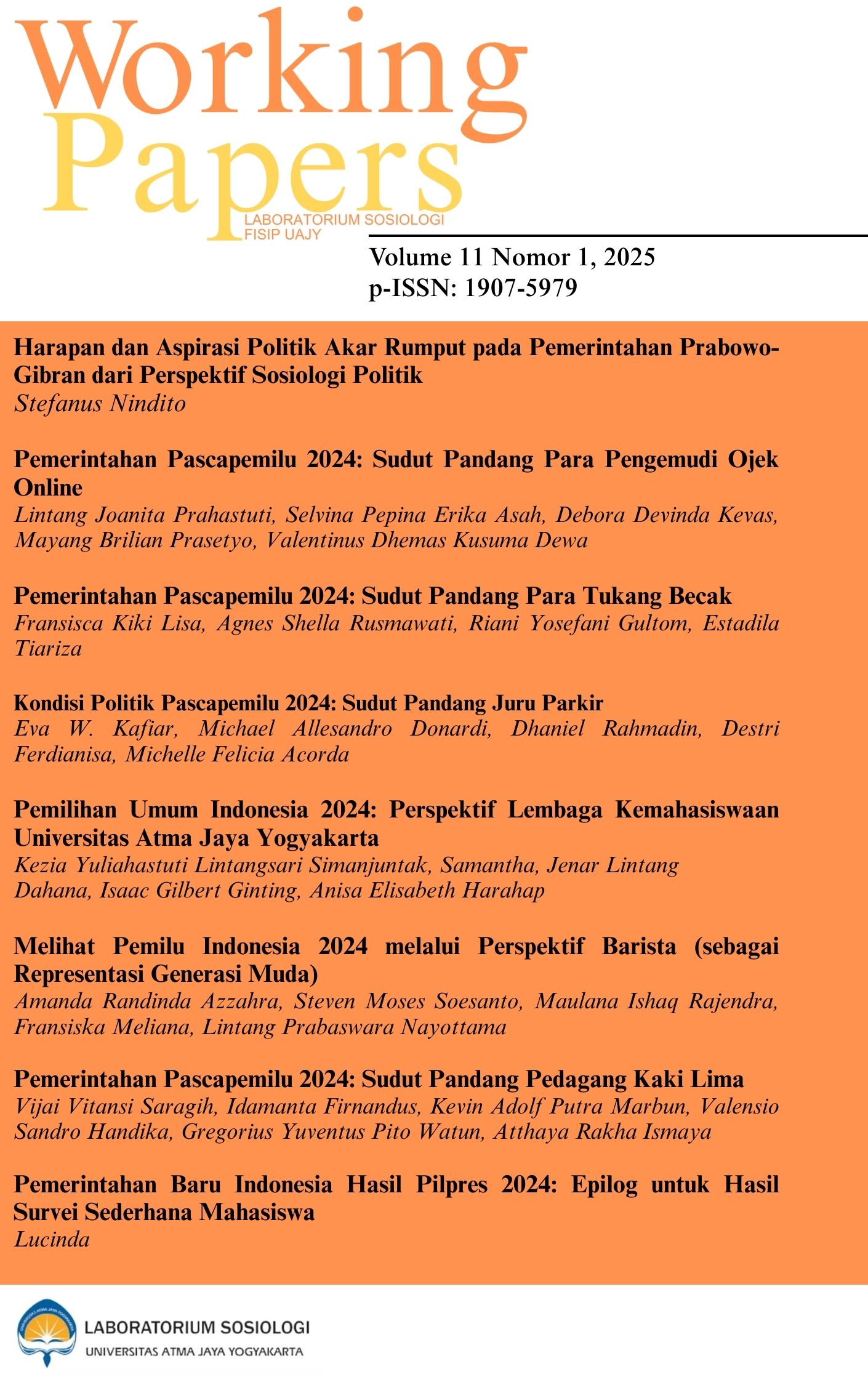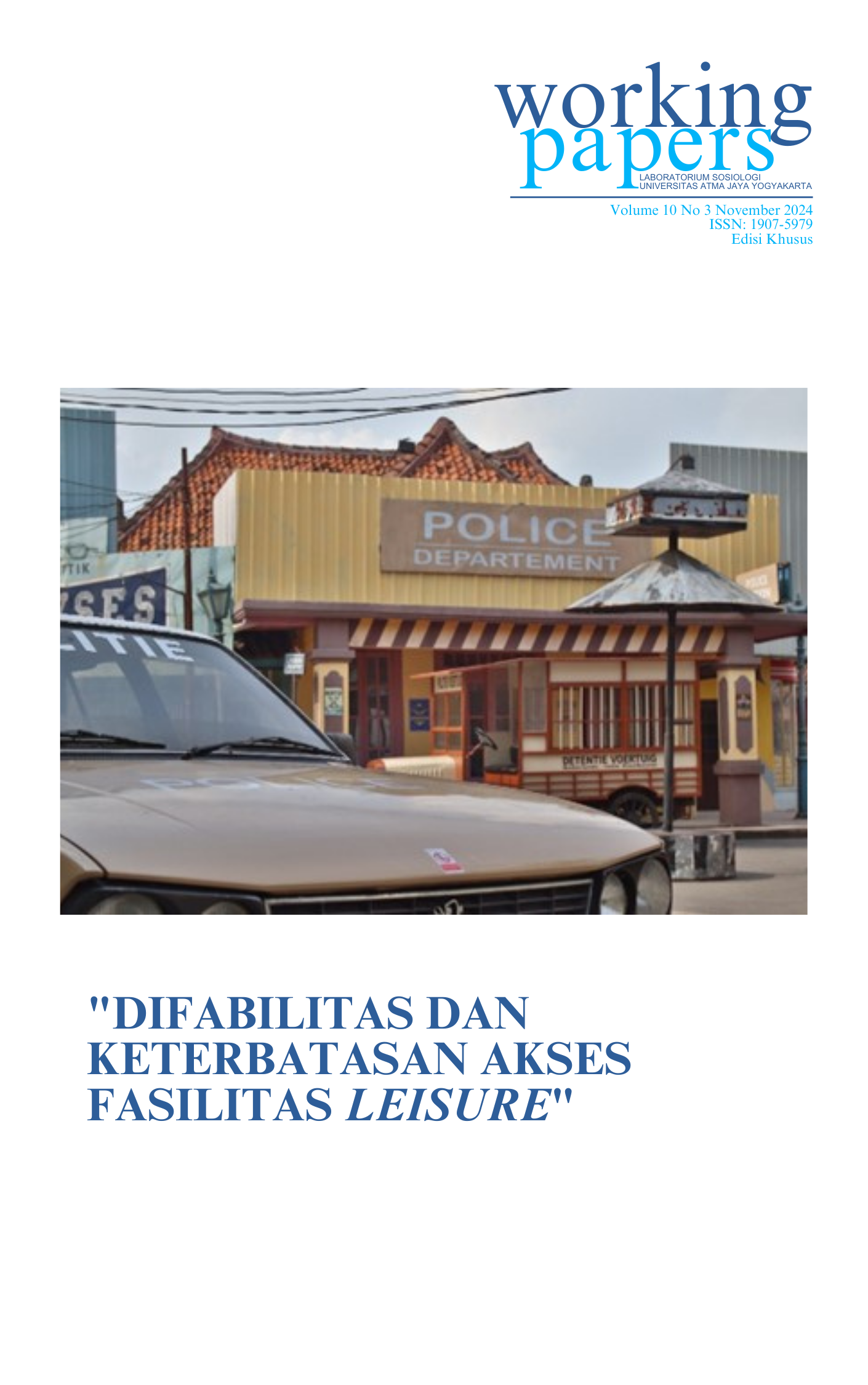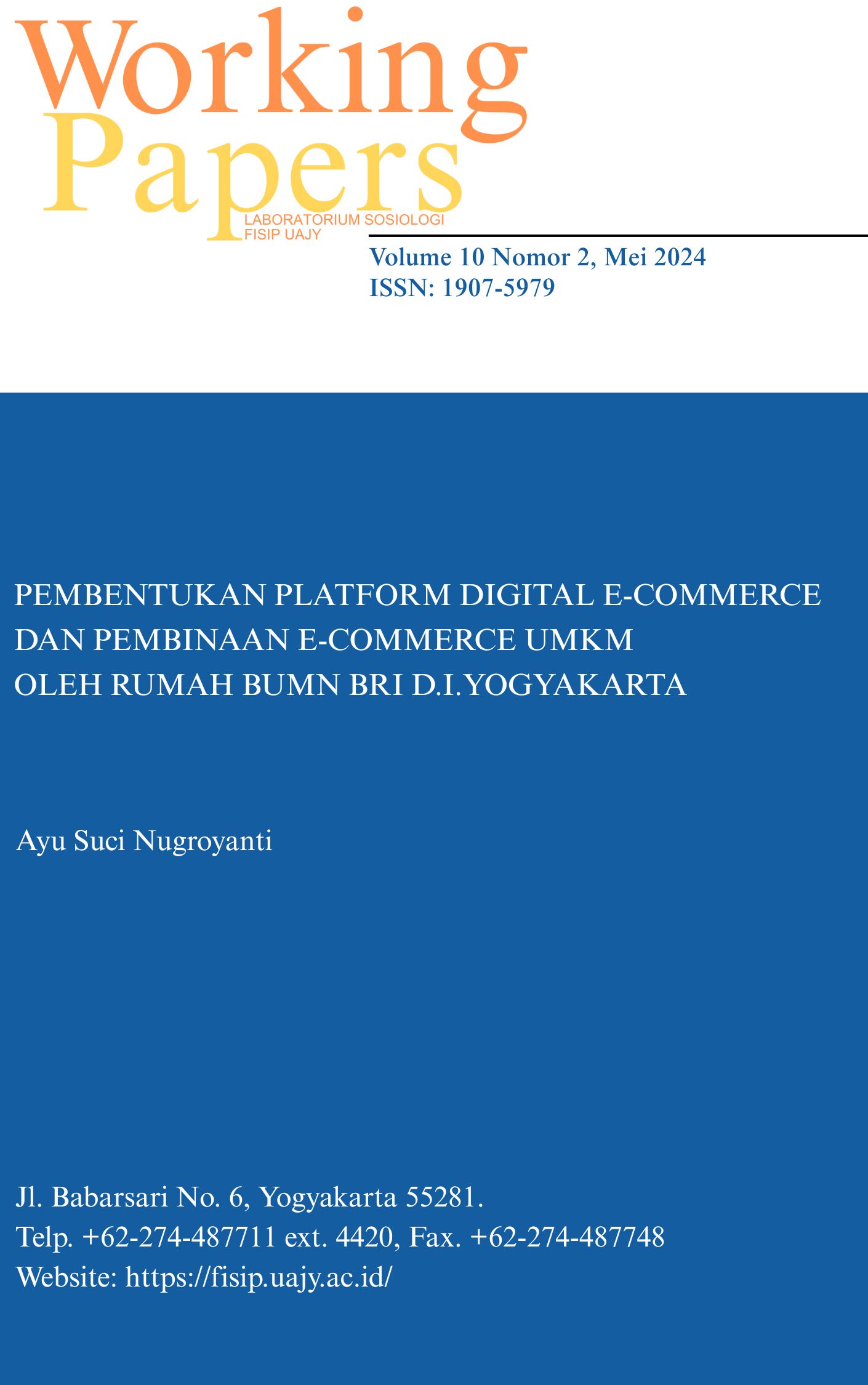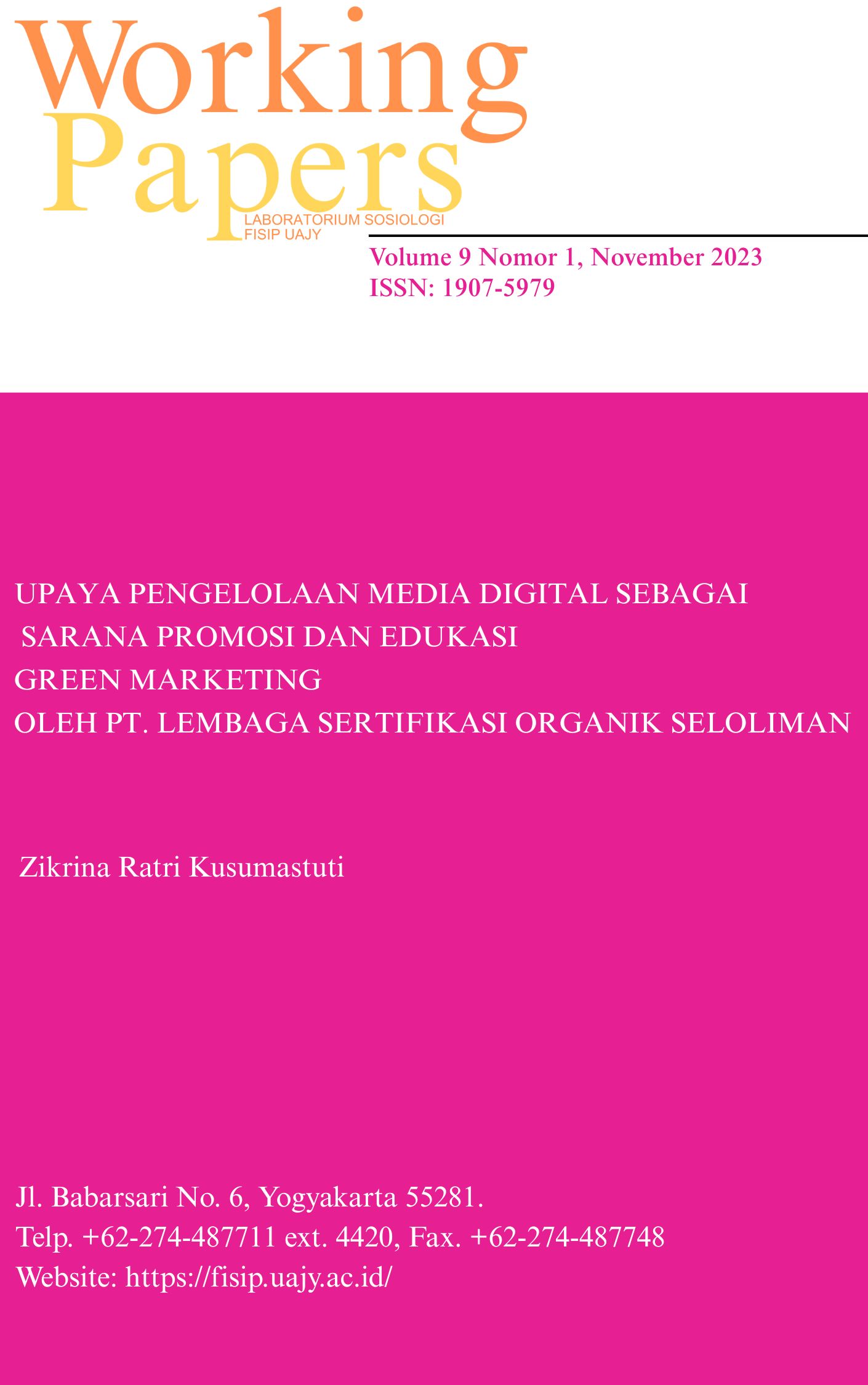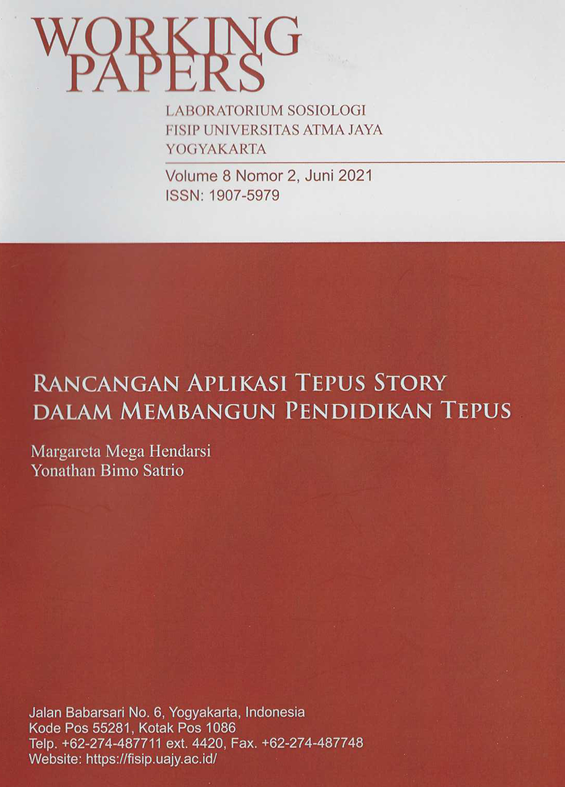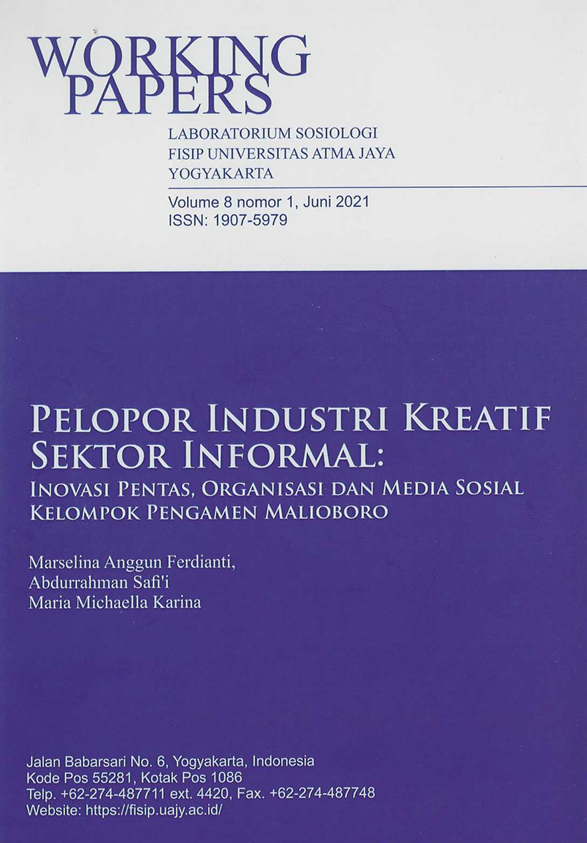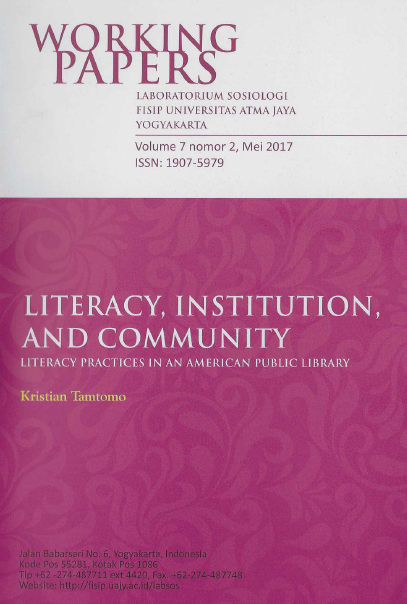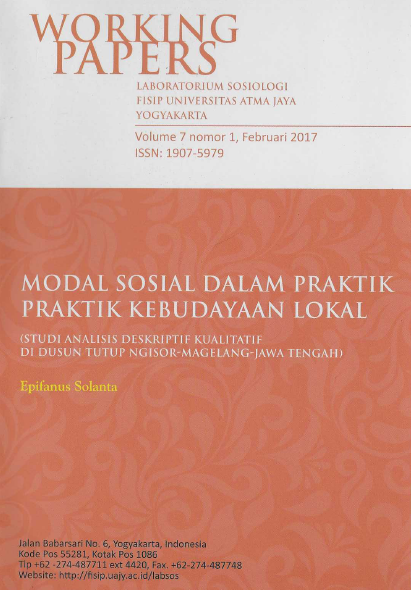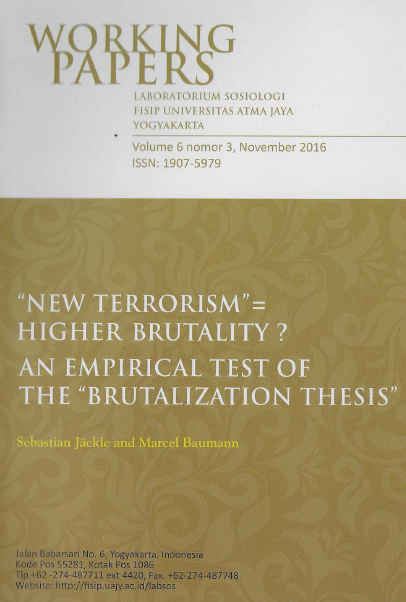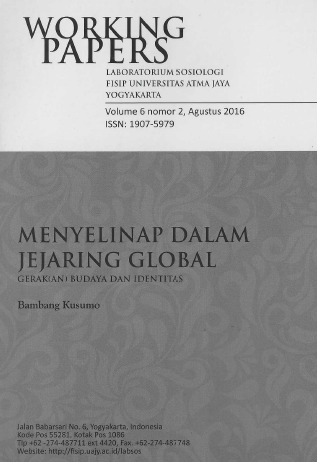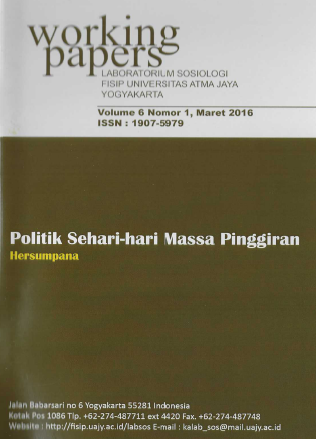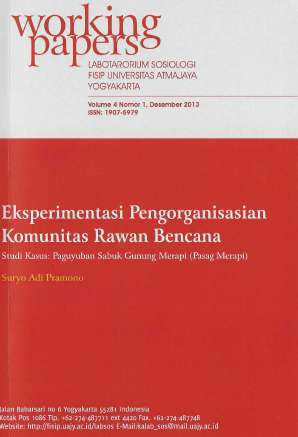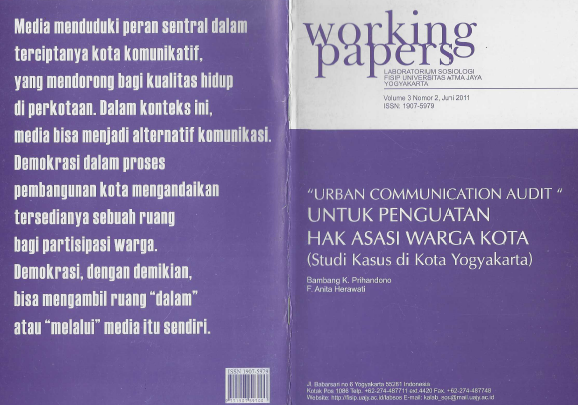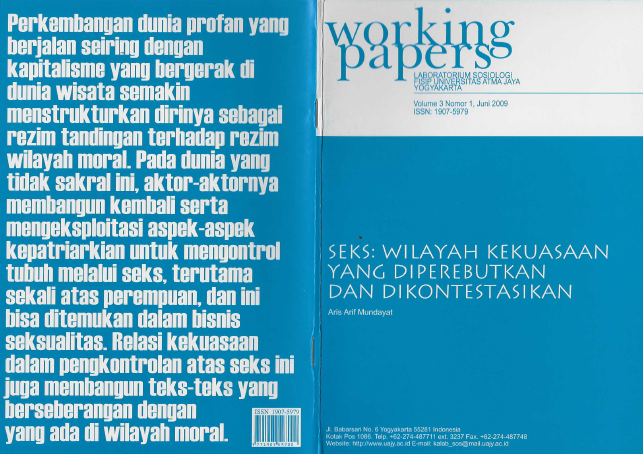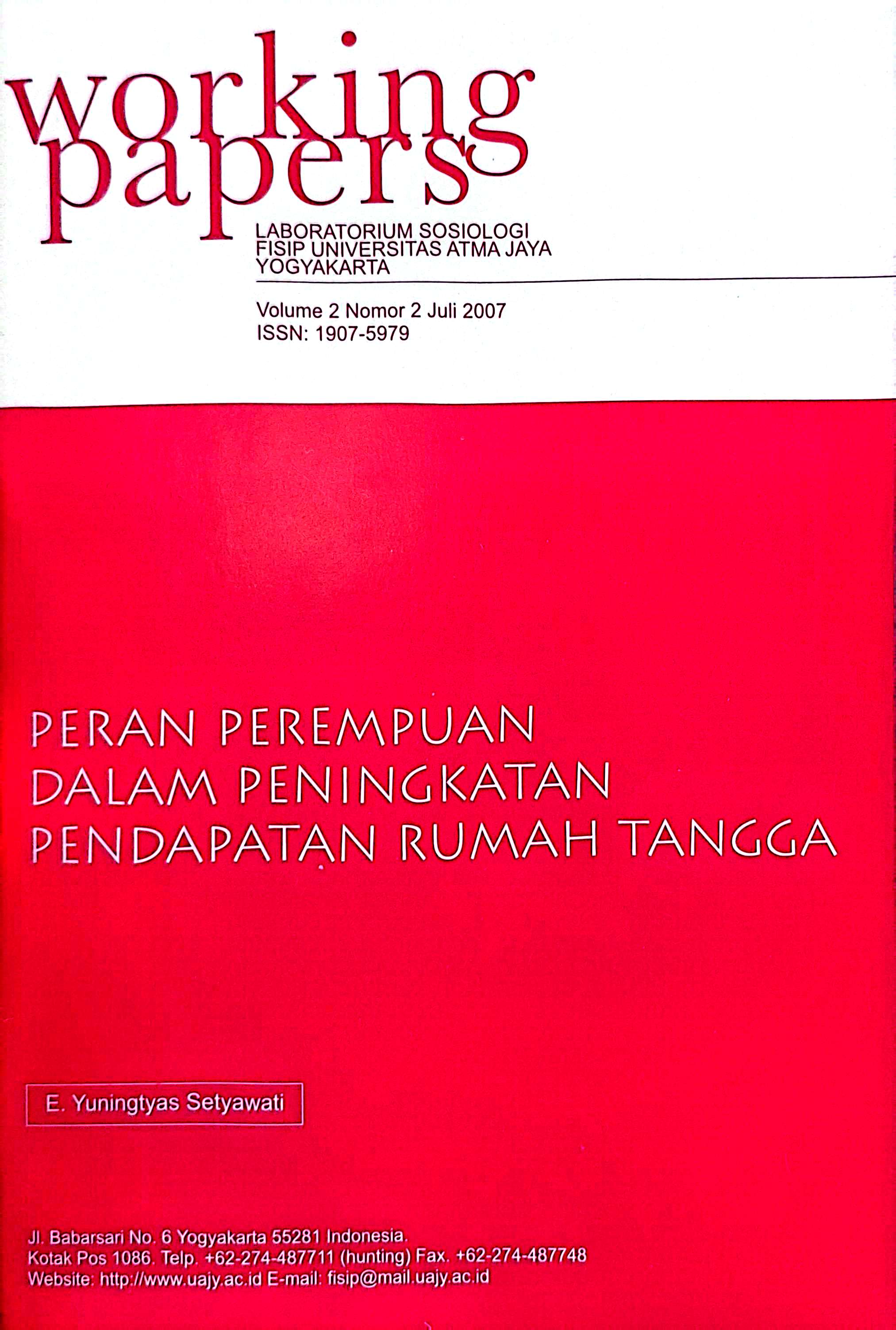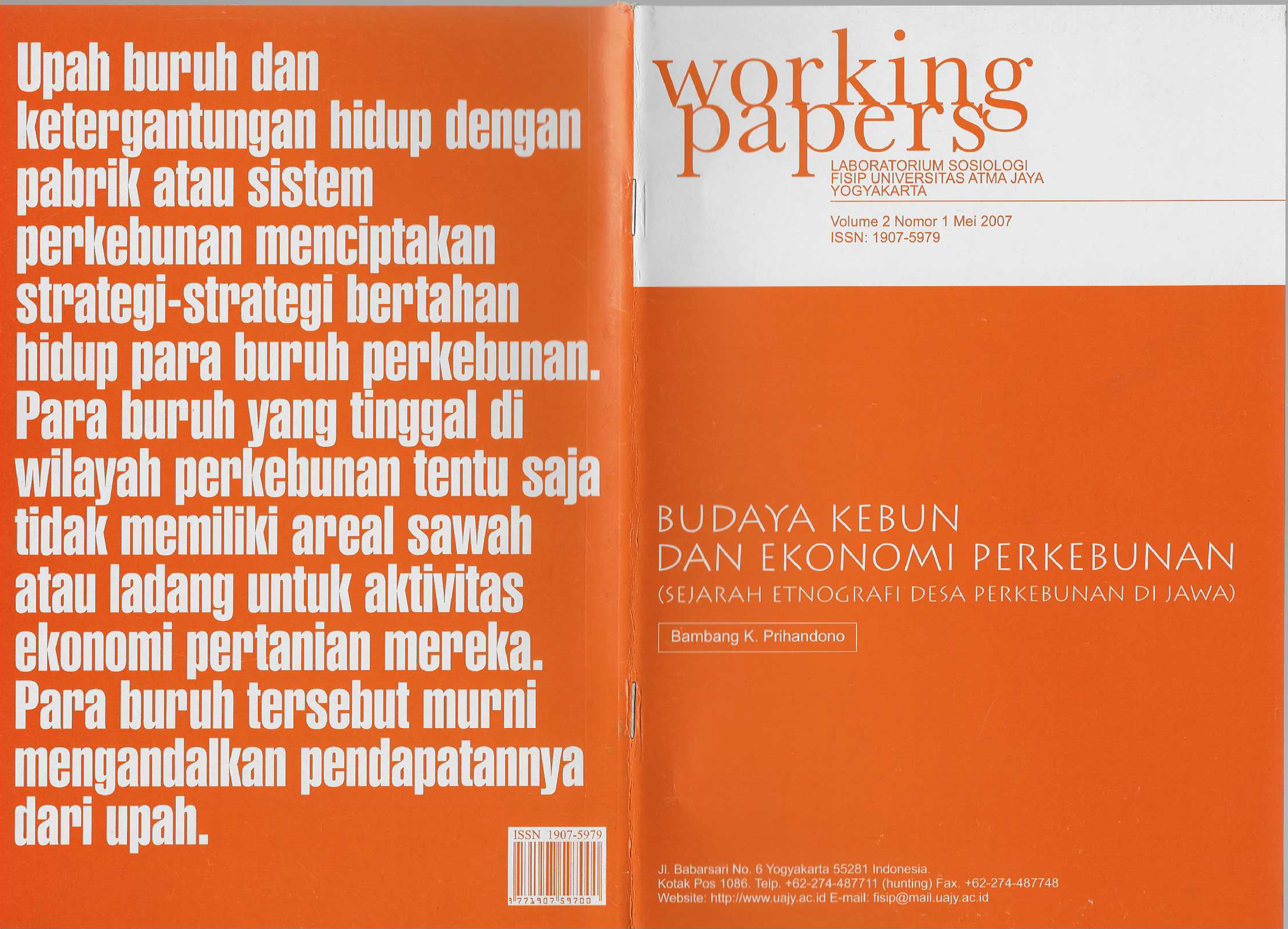Difabilitas dan Keterbatasan Akses Fasilitas Leisure
Vol 10 No 3 (2024)
Akses bagi kelompok difabel sangat diperlukan dalam upaya untuk memberikan rekognisiyang layak terhadap kelompok difabel sebagai bagian dari entitas yang turut hidup bersamadalam ruang urban. Lebih lanjut, kelompok difabel juga perlu dikenali sebagai kelompok yangmemerlukan aktivitas waktu senggang (leisure), di mana aktivitas waktu senggang ini jugaturut berkontribusi terhadap pengalaman hidup sosial kelompok difabel. Karena itu,pembahasan mengenai akses bagi kelompok difabel hendaknya juga mencakup akses terhadapfasilitas bagi aktivitas waktu senggang. Dengan pertimbangan ini, Working PapersLaboratorium Sosiologi UAJY edisi ini akan menyajikan hasil observasi sederhana darimahasiswa Sosiologi UAJY pada Studio Alam Gamplong sebagai salah satu lokasi yang seringdijadikan tujuan bagi aktivitas waktu senggang. Diharapkan sajian visual dan tekstual dalamWorking Papers Laboratorium Sosiologi UAJY ini dapat memberikan sedikit kontribusi padaisu mengenai akses terhadap aktivitas waktu senggang bagi kelompok difabel di erakontemporer ini.
Pembentukan Platform Digital E-Commerce dan Pembinaan E-Commerce UMKM oleh Rumah BUMN BRI D.I.Yogyakarta
Vol 10 No 2 (2024)
Rumah BUMN (RB) sebagai wadah pembinaan dan monitoring perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan pengembangan produk, kualitas, pemanfaatan teknologi dan manajemen. Sebagai wadah pembinaan UMKM Rumah BUMN melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan program pengembangan UMKM dengan menyesuaikan dengan kebutuhan UMKM. Tulisan ini bertujuan menganalisis pembentukan platform digital dan pemanfaatannya dalam proses pembinaan e-commerce UMKM dengan latar belakang yang beragam. Penelitian dengan judul “Pembentukan Platform Digital E-commerce dan Pembinaan E-commerce UMKM oleh Rumah BUMN BRI D.I. Yogyakarta” dilatar belakangi permasalahan UMKM yang tidak hanya berhenti pada pengembangan produk dan proses produksi tetapi berlanjut hingga proses distribusi pemasaran.
Rumah BUMN menjadi Lembaga perantara pengenalan serta sosialisasi penggunaan platform digital bagi UMKM. Studi terhadap permasalahan tersebut dengan menganalisis pembentukan platform digital e-commerce dalam kegiatan pembinaan dengan menggunakan teori SCOT. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan pengumpulan data sekunder. Informan yang dilibatkan dari Rumah BUMN dan UMKM anggota binaan. Pada hasil temuan menunjukkan produksi platform digital e-commerce di Rumah BUMN sebagai konstruksi sosial teknologi dengan memanfaatkan 3 platform e-commerce yaitu e-commerce umum, e-commerce khusus dan sosial media. Platform digital e-commerce membantu proses pembinaan yang dikategorikan menjadi UMKM Go Modern, Go Digital dan Go Online. Platform digital e-commerce dalam pembinaan UMKM sebagai solusi UMKM mengatasi permasalahan pemasaran produk dan membantu UMKM meningkatkan kualitas untuk naik kelas menuju digital ekonomi.
Kata kunci: Platform digital, E-commerce, Pembinaan, UMKM
Mengalami Progresi
Vol 10 No 1 (2024)
Kota merupakan ruang dinamis yang tidak dapat terhindarkan dari progresi. Namun demikian, progresi yang terjadi di lingkungan perkotaan tidak serta merta dialami dengan cara yang sama oleh berbagai lapisan masyarakat. Pluralitas pengalaman atas progresi di lingkungan perkotaan inilah yang menjadi sorotan utama dan dikemas dalam bentuk sajian visual pada buku berjudul "Mengalami Progresi" ini. Dengan harapan agar narasi ini masih mendapatkan tempat dan tidak hilang tergerus oleh kemunculan sekat-sekat dalam kehidupan masyarakat.
Upaya Pengelolaan Media Digital Sebagai Sarana Promosi dan Edukasi Green Marketing Oleh PT. Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman
Vol 9 No 1 (2023)
Lembaga Sertifikasi Organik atau LSO adalah lembaga yang dibentuk untuk menjamin produk organik. LSO yang dibentuk di Indonesia antara lain PT. lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LeSOS). Telah diverifikasi oleh Komisi Akreditasi Nasional (KAN) PT. LeSOS menjalankan perannya sebagai lembaga sertifikasi organik nasional pada empat bidang sertifikasi. Dengan prinsip organik lembaga yaitu memastikan proses produksi produk pertanian organik, meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga keseimbangan ekologis PT. LeSOS ingin menggunakan media digital sebagai alat promosi dan edukasi untuk konsumen ramah lingkungan. Dengan menggunakan green marketing, penelitian kualitatif ini ingin melihat lebih mendalam bagaimana PT. LeSOS secara internal mengimplementasikan Internal Green untuk mengelola marketing communication dan memanfaatkan media digital dan mengelola produksi konten.
Kata kunci: Lembaga sertifikasi organik, green marketing, media digital
Rancangan Aplikasi Tepus Story Dalam Membangun Pendidikan Tepus
Vol 8 No 2 (2021)
Kondisi pendidikan di Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kekurangan dalam bentuk fasilitas. Misalnya bangunan sekolah yang tidak memiliki atap, lantainya hancur, sedikitnya kursi dan meja murid yang tersedia di dalam kelas. Selain itu terdapat kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) karena guru tidak rutin hadir saat mengajar di sekolah. Kurikulumnya masih ketinggalan dengan kurikulum di kota dan mendapatkan buku bekas dari donatur. Kebanyakan murid di Tepus tidak memi-liki semangat belajar, yang disebabkan keterbatasan ekonomi orang tua dan beberapa murid di Tepus merasa tidak memerlukan pendidikan karena mereka akan meneruskan pekerjaan. Orang tua sebagai petani dan peternak. Sedangkan pendidikan sangat penting saat ini tidak hanya dalam pengembangan ke-mampuan intelektual dan pengetahuan, tetapi juga efektif dalam perkembangan untuk membangun karakter anak-anak. Dalam kaitannya dengan Indonesia Emas 2045, pendidikan merupakan media untuk mempersiapkan generasi emas, tidak hanya mentransfer ilmu saja, tetapi nilai-nilai pada karakter individu yang berbasis tiga aspek, yaitu nilai kejujuran, kebe-naran dan keadilan. Oleh karena itu, harus ada upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Tepus. Sudah ada gerakan dari komunitas yang memberikan pendidikan informal untuk anak SD, dengan melakukan pelayanan bimbel pelajaran se-kolah dan moral yang bernama Tepus Story, Komunitas ini melaksanakan kegiatannya menggunakan aplikasi WhatsApp (WA) sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan volunteer, donatur dan untuk mengetahui kabar murid-murid di Tepus. Sedangkan di luar negeri sudah lebih maju dalam menggunakan aplikasi untuk mengorganisir volunteer, donatur dan murid-murid. Salah satu contoh adalah Via Volunteer-South Africa. Maka dari itu kami mengusulkan dan merancang Tepus Story menggunakan aplikasi berbasis Web Site. Dalam penggunaan aplikasi ini terdapat tiga fitur. Fitur pertama adalah fitur anak yang melayani berbagai opsi permainan, opsi PR (Pekerjaan Rumah) untuk mengawasi belajar murid-murid dari jauh karena kegiatan Tepus Story hanya dilakukan seminggu sekali, dan opsi galeri untuk menceritakan kegiatan Tepus Story. Kedua fitur donatur menyediakan tempat pendaftaran bagi donatur Tepus Story dan daftar donatur. Ketiga terdapat fitur volunteer yang menjadi tempat mendaftarkan diri bagi orang yang tertarik menjadi volunteer dan ada list volunteer yang sudah terdaftar dalam fitur tersebut. Ter-akhir fitur Pengurus yang berisi, konfirması donatur sehing ga pengurus dapat mengontrol donasi yang masuk, list ulang tahun guna mengetahui ulang tahun anak-anak yang akan dirayakan, selanjutnya pengurus juga dapat menginput data siswa, volunteer dan donatur. Dengan aplikasi tersebut dapat mengatur kegiatan Tepus Story menjadi efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Tepus
Kata kunci: aplikasi pendidikan, pendidikan informal, pendidikan komunitas
Pioneers of the Informal Sector Creative Industry: Innovations in Performance, Organization, and Social Media of the Malioboro Buskers Group
Vol 8 No 1 (2021)
Keberadaan pengamen jalanan sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat, karena masyarakat merasa sering terganggu dengan keberadaan mereka yang terkadang berlalu-lalang di perempatan lalu-lintas maupun pinggir jalan. Kami ingin menunjukkan bahwa kelompok pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta memiliki ciri khas yang menjadikannya industri kreatif disektor informal. Kelompok pengamen tersebut termasuk ke dalam generasi milenial dengan usia rata-rata di bawah 35 tahun serta pengguna aktif media sosial. Ciri khas dari kelompok pengamen tersebut menggunakan berbagai alat musik yang dibuat dengan kreativitas. Cara pementasan yang membuat penampilan ini berbeda dengan pengamen lainnya yaitu adanya pembagian jam pentas, adanya persiapan, penggunaan kostum dan kolaborasi dengan penari tradisional. Kelompok pemain tersebut menampilkan pertunjukan, dengan membawakan lagu-lagu populer yang dikemas dengan berbagai variasi tanpa meninggalkan unsur budaya lokal. Mereka juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram dan Youtube sebagai ajang untuk mempromosikan budaya dan bisnis dalam bentuk tawaran mengisi acara di berbagai tempat. Berbagai hal inilah yang membuat pengamen di Malioboro terlihat berkualitas dan dapat mengubah stigma masyarakat pada pengamen sebelumnya. Perbedaan dan keunikan yang ditunjukkan oleh pengamen di kawasan Malioboro menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut merupakan sektor industri kreatif berbasis seni dan budaya. Sektor ini berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Yogyakarta karena adanya perizinan serta peraturan yang harus disepakati antara pengamen dan Dinas Pariwisata. Berbagai bentuk kreativitas kelompok pengamen Malioboro ini menjadi potensi industri kreatif yang diharapkan mampu mengoptimalkan generasi milenial untuk mewujudkan generasi emas yang kreatif, produktif serta berkualitas ditahun 2045.
Kata Kunci: Industri Kreatif, Inovasi Kelompok Pengamen, Organisasi, Media Sosial
Literasi, Lembaga, dan Komunitas
Vol 7 No 2 (2017)
Dalam memahami literasi sebagai sebuah praktik sosial, penting untuk mengeksplorasi konteks sosial yang melingkupi pelaksanaan dan keberlangsungan aktivitas literasi. Salah satu aspek penting dari konteks sosial literasi adalah apa yang disebut Long (1993) sebagai “infrastruktur literasi.” Hal ini mencakup berbagai institusi dan aktor yang mendukung atau berperan sebagai “sponsor literasi” (Brandt 1999) pada tingkat kelompok atau komunitas.
Dalam konteks masyarakat Amerika, selain sekolah, perpustakaan umum secara historis memegang mandat sebagai institusi kunci yang berperan sebagai infrastruktur dan sponsor aktivitas literasi di dalam komunitas (Harris 1975). Sebagai sebuah institusi yang menjadi sponsor literasi, perpustakaan memiliki visi dan misi tertentu mengenai jenis-jenis aktivitas literasi yang ingin dipromosikan serta dampak sosial yang diharapkan dari aktivitas literasi tersebut. Namun demikian, sebagai ruang dan konteks praktik literasi, perpustakaan juga menjadi tempat bagi berbagai jenis aktivitas literasi, masing-masing dengan tujuan sosial maupun personalnya sendiri.
Kata Kunci: perpustakaan, institusi, praktik literasi
Modal Sosial Dalam Praktik-Praktik Kebudayaan Lokal (Studi Analisis Deskriptif di Dusun Tutup Ngisor-Magelang-Jawa Tengah
Vol 7 No 1 (2017)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang: (1) Bentuk-bentuk praktek kebudayaan lokal di Dusun Tutup Ngisor; (2) Seni sebagai modal sosial dan modal sosial sebagai Seni dalam praktek kebudayaan lokal; (3) Akumulasi modal sosial berbasis struktur jaringan melalui praktek kebudayaan lokal yang berbasis pada kesenian pertunjukan.
Dalam proses penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dengan beberapa aktor kunci yang ada di Dusun Tutup Ngisor. Selain metode wawancara, juga menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion) yang dilaksanakan bersama warga serta berpartisipasi secara aktif. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka di perpustakaan dan juga di internet. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan kategori data serta proses trianggulasi. Di samping itu, dalam proses pemetaan jaringan sosial, penulis menggunakan metode analisis sosiometrik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Bentuk-bentuk praktek kebudayaan lokal yang ada di Dusun Tutup Ngisor antara lain: pementasan wajib empat kali dalam setahun, pemberian sesaji, pertunjukan Dewi Sri dan Gamelan malam Jumat. (2) Praktek kebudayaan lokal tersebut berkembang dikarenakan oleh kekuatan modal sosial dan struktur jaringan dengan institusi pemerintah, gereja, sekolah, media dan komunitas seni (3) Bentuk modal sosial diantaranya partisipasi, kerja sama kelompok, norma sosial, kepercayaan dan resiprositas.
Kata Kunci: Seni, Modal Sosial, Struktur Jaringan dan Kebudayaan Lokal
"Terorisme Baru" = Kebrutalan yang Lebih Tinggi? Sebuah Uji Empiris terhadap "Tesis Brutalisasi"
Vol 6 No 3 (2016)
Artikel ini berfokus pada apa yang disebut sebagai “brutalisasi” terorisme. Tesis brutalisasi, sebagai bagian dari konsep teoretis yang lebih luas mengenai “terorisme baru”, berpendapat bahwa “terorisme baru” lebih brutal dibandingkan dengan “terorisme lama.” Banyak sarjana mengklaim bahwa serangan 9/11 menandai awal dari era baru terorisme yang telah mengangkat terorisme internasional maupun domestik ke tingkat kebrutalan kekerasan yang baru. Namun, pihak lain berpendapat bahwa proses ini sebenarnya sudah dimulai sejak awal 1990-an. Setelah membahas kemungkinan cara untuk mengoperasionalisasikan konsep brutalisasi terorisme—misalnya dengan berfokus pada bom bunuh diri atau serangan teroris terhadap soft targets (sasaran empuk)—artikel ini menguji kredibilitas empiris dari tesis brutalisasi dengan mempertimbangkan kedua titik awal potensial tersebut. Data dari Global Terrorism Database (GTD) menunjukkan bahwa hanya tiga dari sembilan indikator yang meningkat secara signifikan selama tahun 1990-an. Hal ini sebagian mendukung gagasan adanya brutalisasi secara umum, sementara meningkatnya jumlah serangan bunuh diri dan pemenggalan kepala setelah 9/11 mendukung gagasan adanya perubahan kualitatif dalam terorisme dan kebrutalannya, yang berkaitan dengan upaya memaksimalkan perhatian media dan publik. Namun demikian, perkembangan ini terbatas secara regional, dan kebrutalan dari “terorisme baru” ini hanya melampaui tingkat yang dikenal dari puncak “terorisme lama” pada tahun 1970-an dan 1980-an dalam beberapa kasus saja.
Kata kunci: Brutalisasi; Global Terrorism Database (GTD); Pemenggalan Kepala; Sasaran Empuk; Serangan Bunuh Diri; Terorisme Baru;
Menyelinap Dalam Jejaring Global: Gerakan Kebudayaan dan Identitas
Vol 6 No 2 (2016)
Politik Sehari-hari Massa Pinggiran
Vol 6 No 1 (2016)
Perkembangan kota adalah sebuah peluang bagi peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi bagi yang tidak bisa memanfaatkan peluang tersebut, baik pendatang maupun penduduk lokal menjadi kelompok pinggiran Kelompok periferial tidak bisa masuk dalam sistem modernitas kehidupan kota. Kelompok pinggiran ini mempunyai cara untuk bertahan (survived). Komunitas Bong Suwung membangun siasat ekonomi dan politiknya sendiri dalam menghadapi modemitas kota yang di mata pemangku kekuasaan dipandang sebagai kelompok pengganggu dan citra hitam kota". Meskipun demikian, ada relasi antara kekuasaan yang terjalin secara tidak kasap mata antars penguasa dengan komunitas yang dipandang illegal. Fenomena beking merupakan bagian dari siasat yang berkembang dalam kehidupan seperti Bong Sowung yang diwakili oleh "oknum aparat militer dengan kelompok komunitas illegal seperti yang digambarkan oleh Edward Aspinal dan Gerry Van Klinken yang disebut dengan "enthrenched illegality" Bagian ini mendiskusikan lebih lanjut siasat politik sehari-hari komunitas Bong Suwung dan transformasi komunitas di tengah perkembangan kota Yogyakarta dalam hubungannya dengan kekuasaan negara.
Seks: Wilayah Kekuasaan yang Diperebutkan dan Dikontestasikan
Vol 3 No 1 (2009)
Berangkat dari data lapangan yang berupa studi kasus dari dua orang perempuan di Sukabumi (Jawa Barat) dan Sanur (Bali), tulisan ini mendiskusikan masalah seksualitas dan otoritas ketubuhan perempuan dalam dunia sosial. Ketubuhan perempuan dalam hal ini tidaklah secara serta merta merupakan tubuh terdominasi, namun lebih merupakan ranah seksualitas yang diperebutkan dan dikontestasikan kemaknaannya bagi dunia sosial yang terdiri dari perempuan dan laki-laki.
Peran Perempuan Dalam Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga
Vol 2 No 2 (2007)
Mata pencaharian nelayan dapat dijadikan tumpuan ekonomi bagi rumah tangga nelayan di samping pekerjaan di sektor pertanian. Meskipun pendapatan yang dihasilkan nelayan di sekitar Pantai Ngrenehan saat ini belumlah cukup menggembirakan. Namun demikian pekerjaan di sektor perikanan mampu menjadi alternatif lain dari sektor pertanian yang lebih menguntungkan. Untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, maka istri nelayan biasanya turut serta dalam aktivitas perikanan. Aktivitas yang dilakukan oleh istri nelayan adalah berjualan ikan hasil tangkapan dan membuka warung-warung makan di sekitar pantai. Pendapatan istri nelayan biasanya jauh lebih tinggi daripada suami mereka, saat sepi saja rata-rata pendapatan istri nelayan Rp. 20.000,- hingga Rp. 30.000,- perhari, namun ketika hari libur seperti Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional pendapatan mereka jauh lebih banyak. Sementara suami mereka setiap kali selesai melaut hanya memperoleh upah pendapatan rata-rata Rp. 50.000,-, apalagi kalau hasil tangkapan ikannya hanya sedikit sekali mereka tentunya akan lebih merugi. Besarnya kontribusi peran publik perempuan tidaklah mengurangi peran domestiknya, curahan waktu perempuan di sektor domestik dan publik menunjukkan rata-rata: perempuan mencurahkan waktu 13-15 jam sehari untuk melakukan pekerjaan domestik dan publik sekaligus. Sementara curahan waktu laki-laki sebanyak ± 8-10 jam sehari, bila diasumsikan laki-laki hanya bekerja di sektor publik dan tidak terlibat dalam pekerjaan domestik. Dengan demikian peran gender dalam rumah tangga masih nampak orientasi pada bias gender, sehingga perlu adanya penyadaran gender agar dapat terwujud kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Hal ini berguna untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang dimiliki baik laki-laki maupun perempuan.
Kata kunci: peran gender, kemitrasejajaran laki-laki perempuan, dan ekonomi rumah tangga
Budaya Kebun dan Ekonomi Perkebunan (Sejarah Etnografi Desa Perkebunan Di Jawa)
Vol 2 No 1 (2007)
Kolonialisme merupakan faktor penting dalam pembentukan sistem perkebunan di Indonesia sebagai sistem sosial-ekonomi yang baru. Ekonomi politik pertanian kolonial memperkenalkan sistem baru di wilayah-wilayah lokal, mengubah sistem ekonomi dari subsistensi pedesaan menjadi pertanian berorientasi ekspor. Dalam kasus wilayah Kendeng Lembu, khususnya pada masa pascakolonial, fluktuasi dalam perkembangan perkebunan berkaitan dengan proyek dekolonisasi di bidang politik dan ekonomi. Meskipun telah terjadi proses dekolonisasi, sistem dan struktur sosial di perkebunan Kendeng Lembu tampaknya merupakan tiruan dari warisan sistem perkebunan kolonial.